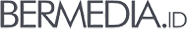Masing-masing pihak bebas menentukan sikapnya, termasuk Menko PMK Muhadjir Effendy yang menilai fenomena CFW bersifat sementara: jika warga sudah bosan, maka akan bubar sendiri. Sayang sekali, CFW dan SCBD tidak dipandang sebagai kesempatan untuk mengembangkan subkultur baru yang inovatif dan positif bagi kalangan muda, terutama mereka yang termarjinalisasi di sekitar megapolitan Jakarta. Orientasi pejabat pemerintah yang mengurus masalah pembangunan sumberdaya manusia dan kebudayaan mewakili arus utama modernisme yang serba-tertib dan terukur.
Istilah postmodernist, pertama kali dilontarkan Arnold Toynbee pada tahun 1939 lewat buku masterpiece berjudul Study of History. Modernisme dan juga posmodernisme hanya penggalan sejarah manusia yang bisa berubah posisi, tergantung dari perspektif pembacaannya. Lyotard yang lahir pada 1924 di kota kecil Versailes, sebelah selatan kota Paris, kemudian menghadapi goncangan budayay tatkala bertugas mengajar di sekolah menegah di kota Konstantine, Aljazair Timur pada tahun 1950 – 1952. Ia menyaksikan sendiri kegagalan peradaban (modernisme) Barat yang berujung pada kolonialisme dan imperialisme. Karir Lyotard dilanjutkan dengan menjadi profesor filsafat di Universitas Paris VII.
Subkultur
Kaum muda Sawangan, Citayam, Bojong Gede dan Depok memang hanya iseng membentuk subkultur baru di pusat megapolitan Jakarta. Bahkan, sebutan SCBD dan CFW bermula dari kalangan netizen sebagai bahan ejekan. Tak tampak idealisme, apalagi ideologi, yang mendasarinya. Namun, itu bukan berarti kaum muda sekarang (Gen Z) sama sekali kosong dari idealisme. Beberapa tahun lalu kita menyaksikan anak-anak STM yang mendukung gerakan mahasiswa untuk melakukan perubahan dan menolak oligarki. Mereka terbukti militan dan kompak, bahkan ada kelompok muda yang lebih jauh terlibat dalam gerakan anarko.